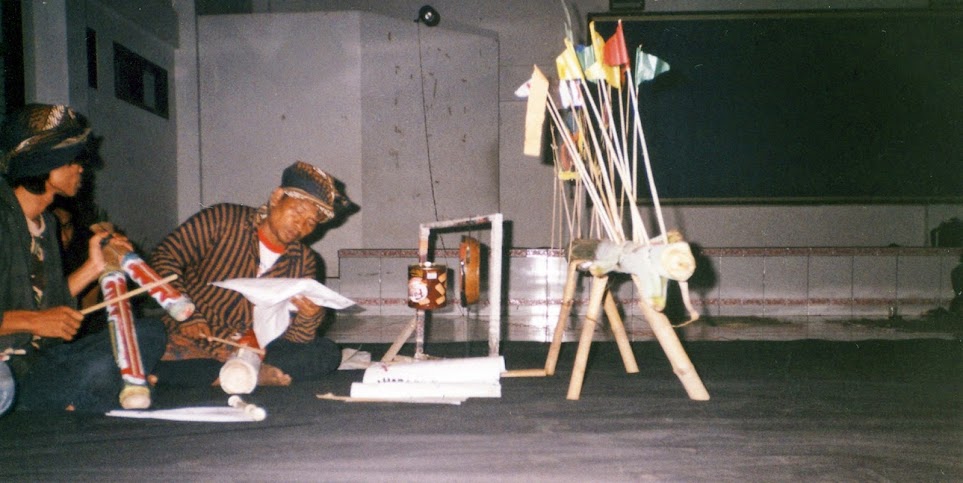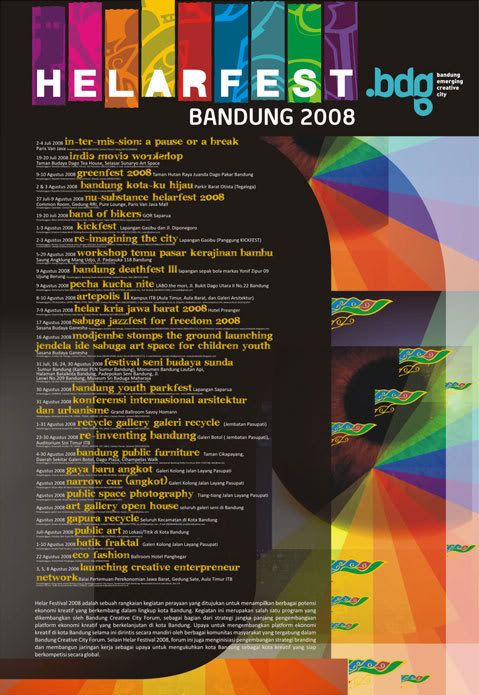Tampilkan postingan dengan label Budaya. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Budaya. Tampilkan semua postingan
Rabu, 19 Februari 2014
Ketika Jakarta Ingin Seperti Harajuku
Rabu, Februari 19, 2014
Budaya, busana, cinta, Gerakan, Indonesia Kreatif, Industri/ Ekonomi Kreatif, kearifan lokal, produk lokal, ramah lingkungan
No comments
Harajuku adalah
satu pusat busana jalanan yang kini telah terkenal di seluruh penjuru jagad
raya ini. Di lokasi ini ada beragam butik, mal-mal yang memajang beragam busana
serta semua hal yang berkait dengan dunia busana. Harajuku adalah sebuah
kampung kecil yang berubah menjadi pusat busana dan budaya kaum muda pasca
Perang Dunia II. Adanya barak militer tentara Amerika Serikat di Bukit
Washington membawa dampak yang cukup besar bagi kaum muda setempat dalam
berbudaya Barat. Apalagi setelah penyelenggaraan Olimpiade 1964 yang menjadikan
Harajuku sebagai lokasi perkampungan atlet, proses asimilasi budaya semakin
kuat. Sejak berdirinya mal khusus busana pada 1978, Harajuku seolah memantapkan
posisinya sebagai pusat bisnis busana dunia dengan konsep jalanan-nya.
Indonesia Fashion Week (Pekan Busana Indonesia) yang akan
diselenggarakan di jakarta Convention Center 20 – 23 Pebruari 2014 adalah
sebuah ajang kreatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Sebagai motor
penggerak adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang didukung oleh
tiga kementerian terkait yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi
dan UMKM serta Kementerian Perindustrian yang mengusung tema besar Green
and Local Movement. Tema yang intinya mengajak seluruh lapisan
masyarakat untuk mencintai produk-produk lokal (buatan dalam negeri) dan yang
ramah lingkungan.
Indonesia Fashion Week mengajak warga Jakarta untuk ramai-ramai
memamerkan gaya lokal terbaiknya pada tanggal 16 Februari 2014 lalu melalui event Sunday Dress Up. Aksi yang
didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini telah berlangsung
pada saat Car Free Day di bundaran HI
hingga area Monas. Ratusan partisipan dari berbagai komunitas umum melebur
bersama desainer, model, pelaku media hingga murid sekolah mode. Mereka memakai
busana bernuansa konten lokal dan melakukan "demo" dengan membawa slogan-slogan
seputar local movement.
Dengan Local MovementLocal Movement, Indonesia Fashion Week akan semakin memperkuat rasa
cinta dan bangga pada negeri sendiri beserta produknya. Berbagai rangkaian
pra-event yang seru dan penuh energi segar seperti Sunday Dress Up ini
diharapkan dapat memperkenalkan "gaya Indonesia" kepada dunia. Sudah
saatnya kita bangga memakai produk yang menunjukan identitas diri kita.
Indonesia yang kaya akan material, detail hingga styling, punya ciri fashion
tersendiri yang berbeda dibandingkan dengan ciri fashion yang sudah ada di dunia.
Mungkin suatu hari nanti di Jakarta
akan ada area khusus seperti di Harajuku-Jepang, dimana semua orang dapat
"memamerkan" gaya lokalnya masing-masing. Lalu perlahan tapi pasti,
warga dunia akan menoleh pada "gaya lokal" Indonesia. Dan kita pun
dapat berkata dengan bangga,"Gaya ini adalah gaya lokal Indonesia!". Mimpi itu dimulai dari sekarang, dan kita
semua ikut andil dalam mewujudkannya!
Itulah obsesi Jakarta yang selama
ini telah menjadi barometer kehidupan di tanah air. Selain merupakan ibukota
negara dan pusat pemerintahan, Jakarta juga menjadi pusat beragam aktivitas
bisnis. Di bidang busana, selain Tanah Abang yang telah menjadi pusat bisnis
busana kelas menengah-bawah, banyak pusat busana yang ada di berbagai mal dan
pusat belanja kelas menengah-atas yang tersebar di seantero Jakarta.
Rumah-rumah mode dan toko-toko online yang menyediakan busana beragam keperluan
dan harga terus bertumbuh. Belum lagi sejumlah konveksi, modiste dan tailor.
Semua itu merupakan faktor pendukung yang sangat kuat bagi tumbuh dan
berkembangnya bisnis busana.
Dengan pengakuan Unesco bagi batik
tulis Indonesia sebagai warisan budaya dunia (world herritage) semakin menambah rasa percaya diri para perancang
dan pebisnis busana untuk terus memantapkan diri dan industri kreatif ini ke
posisi puncak. Pekan Busana Indonesia memang layak diapresiasi sebagai satu
jalan utama untuk menggapai asa Jakarta setara dengan atau lebih tinggi dari
Harajuku di Jepang. Diperluat dengan gerakan lokal dan ramah lingkungan (local and green movement) serta upaya
serius menumbuh-kembangkan Sentra-Sentra Kreatif Rakyat di berbagai daerah
tujuan wisata unggulan, bukan satu hal yang mustahil jika tak lama lagi ada
Harajuku ala Jakarta. Tentunya dengan satu harapan besar lain, situasi politik
dalam negeri cukup kondusif. Semoga.
Kamis, 11 April 2013
FIESTA de LUK ULO (Konsep Ringkas - Update)
Kamis, April 11, 2013
Aset, Budaya, Creative City, Festival, Forum, Hanito Kreasindo, Industri/ Ekonomi Kreatif, Kebumen, Kegiatan, keraifan budaya, Kerajinan Tangan, Kreatif, Seputar Hipando, Wacana
No comments
Konsep festival dipilih agar
beberapa kegiatan dapat dicakup serentak. Ada wisata air seperti lomba
pacu rakit berbahan batang pisang (gedebog) dan aneka permainan anak yang
menjadi ciri khas permainan anak pereng Kali Luk Ulo. Lomba Mancing yang
menjadi “gong” berpadu dengan Festival Kuliner dan lain-lain. Konsep festival
membuka peluang beragam kegiatan dikemas dalam satu wadah “Luk Ulo Fiesta 20,,,”.
MAKSUD dan TUJUAN
Festival Kali Luk Ulo tahun 20.., dimaksudkan
untuk :
- Memberikan hiburan murah dan aman bagi warga masyarakat Kabupaten Kebumen dan sekitarnya.
- Mengenalkan Kali (Sungai) Luk Ulo sebagai salah satu icon aktivitas kreatif Kabupaten Kebumen.
- Pendidikan lingkungan bagi generasi muda.
- Pengembangan kegiatan wisata lingkungan.
- Perintisan dan pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kebumen.
Tujuan utama
kegiatan ini adalah mengembangkan potensi kreatif para pemuda Kebumen dalam
beragam kegiatan produktif dan
kewirausahaan yang ramah lingkungan.
KONSEP FESTIVAL
Festival adalah
kegiatan yang menampilkan kemeriahan yang dapat diisi dengan beragam jenis
kegiatan saling berkait. Festival Kali Luk Ulo 2012 adalah perpaduan antara
kegiatan olahraga, hiburan, wisata, pendidikan lingkungan dan kewirausahaan.
Ada 2 jenis kegiatan olahraga yang akan dilaksanakan yakni Lomba Mancing Ikan Bersisik dan
outbond.
Hiburan akan diisi
dengan lomba permainan anak tradisional seperti kunclungan, mengambang di air dengan sarung terlama dan lain-lain.
Atau atraksi kesenian tradisional yang akan diselenggarakan di sekitar lapangan
basket dan bekerjasama dengan Kelenteng Khong Hui Kiong. Kegiatan hiburan ini
dapat juga dikembangkan dengan beragam festival, lomba atau penampilan
kelompok-kelompok kesenian yang potensial dikembangkan sebagai aset
ekonomi kreatif masyarakat Kabupaten Kebumen.
Sementara itu,
pendidikan lingkungan dilaksanakan dengan cara memberikan pemahaman, bimbingan
dan praktik di sepanjang lokasi festival yang direncanakan sepanjang 1 km.
Mulai dari bawah Jembatan Kutosari (jembatan baru di Selatan Alun-alun kota)
sampai Jembatan Renville (jembatan kereta api). Pendidikan lingkungan ini
bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan mencerahkan pemahaman tentang
pentingnya memelihara lingkungan alam Kali Luk Ulo di sepanjang jalur
festival khususnya dan daerah alirah Sungai Luk Ulo pada umumnya.
Dalam kegiatan
kewirausahaan, akan diselenggarakan festival kuliner berbahan dasar ikan
bersisik yang hidup dan berkembang biak di Kali Luk Ulo yang mengikutsertakan
para petani ikan yang banyak beraktivitas di sebelah Utara lokasi. Serta
beberapa kegiatan lain yang menunjang tujuan pengembangan ekonomi kreatif warga
masyarakat sekitar lokasi festival khususnya.
Jumat, 05 April 2013
Bandung Creative City Forum (BCCF)
Jumat, April 05, 2013
aktivitas, Bandung, Budaya, Creative City, Forum, Industri/ Ekonomi Kreatif, Inspiratif, kepedulian Pemerintah, Lokal, Obesesi, Sadar Wisata, Wacana
1 comment
Bandung kota kreatif bukan hanya slogan dan baru
dirintis. Sejak dulu, Kota Kembang yang sering disebut juga sebagai Paris van
Java telah menunjukkan beragam aktivitas kreatif warganya. Di era 1980-an, jauh
waktu sebelum ekonomi/ idustri kreatif digagas, Bandung sudah punya Depot
Kreasi Seni Bandung (DKSB) dengan alm. Harry Rusli sebagai motornya dari
rumahnya di Jl. Supratman sebagai markas besar. Dari grup musik eksperimental ini muncul satu single
hit berjudul Nyamuk Malaria. Sementara itu, di ujung jalan itu ada beragam
jenis kuliner khas yang menjadikan daerah Supratman Ujung sebagai pusat jajanan
khas Bandung. Musik, seni pertunjukan dan kuliner adalah pilar ekonomi kreatif
yang tengah menjadi trend baru ekonomi di banyak Negara.
Bandung Ibukota Kreativitas?
Reputasi Bandung
sebagai destinasi wisata, lokasi perguruan tinggi terkemuka, pusat mode dan
busana, serta kota yang melahirkan beragam band/kelompok musik progresif, telah
berdampak pada tumbuhnya industri kreatif yang didukung oleh ketersediaan
beragam sumber daya. Bandung jadi Ibukota Kreatif?
APA sih yang kurang
dari Kota Bandung sebagai kota kreatif? Rasanya semua persyaratan untuk menjadi
kota kreatif sudah dimilki Bandung. Sebut saja, hampir seluruh profesi kreatif
bisa ditemukan di Bandung, sejak profesi yang high profil seperti arsitektur,
clothing dan distro, pembuat program komputer, animator, hingga pemBuat film dan
musik. Belum lagi iklim yang mendukung, dengan banyaknya pagelaran dan hajatan
kreatif yang digelar dan sepanjang tahun. Untuk yang terakhir ini, para pegiat
kreatif Bandung sudah dua kali menggelar hajatan Helarfest, tahun 2008 dan
2009. Tahun 2010, ada Semarak.bdg yang digelar di sekitar kawasan Braga. Belum
lagi gelaran seperti Bandung World Jazz Festival, dan Pasar Seni ITB.
Situs Departemen Perdagangan menginformasikan industri kreatif menyumbang rata-rata 6,3% terhadap produk domestik bruto Indonesia selama periode 2002-2006. Suatu jumlah yang tidak main-main karena pada 2010, target kontribusi meningkat menjadi 7,9%. Setelah kekayaan sumber daya alam tidak lagi dapat menjadi penopang perekonomian nasional, ditambah sulitnya produk sektor usaha berbasis sumber daya alam lainnya bersaing dengan negara lain karena kalah kompetitif, maka masa depan Indonesia mungkin hanya bisa diselamatkan melalui ekonomi kreatif yang berbasis kekuatan ‘human capital’ yang kreatif dan inovatif.
Situs Departemen Perdagangan menginformasikan industri kreatif menyumbang rata-rata 6,3% terhadap produk domestik bruto Indonesia selama periode 2002-2006. Suatu jumlah yang tidak main-main karena pada 2010, target kontribusi meningkat menjadi 7,9%. Setelah kekayaan sumber daya alam tidak lagi dapat menjadi penopang perekonomian nasional, ditambah sulitnya produk sektor usaha berbasis sumber daya alam lainnya bersaing dengan negara lain karena kalah kompetitif, maka masa depan Indonesia mungkin hanya bisa diselamatkan melalui ekonomi kreatif yang berbasis kekuatan ‘human capital’ yang kreatif dan inovatif.
Lantas,
dari angka kontribusi 7,9 % ini, seberapa besar yang disumbang Bandung? Meski
tidak tersedia data yang cukup memadai, namun diyakini Bandung berkontribusi
dominan. Terlebih, karena para pegiat di Bandung juga sudah memiliki kesadaran
untuk beserikat dan berorganisasi dalam payung Bandung Creative City Forum atau
BCCF.
Bandung
Creative City Forum (BCCF) yang berdiri sejak tahun 2008, beranggotakan para
pegiat kreatif dari beragam latar belakang profesi antara lain arsitek,
desainer, pekerja seni, pekerja musik, akademisi, praktisi & pekerja TI,
pelaku usaha pariwisata, dan jurnalis. Seluruh
kegiatan BCCF bersifat nirlaba dan diperuntukan sepenuhnya untuk pengembangan
kota Bandung dalam bidang dan karya kreatif. BBCF juga merupakan mitra
strategis Pemerintah Kota Bandung dalam membawa Bandung sebagai kota kreatif
dengan kompetensi internasional di benua Asia.
Tujuan
untuk menjadikan Bandung sebagai ibukota kreatini bukan hal yang mustahil untuk
diwujudkan. Semangat ini, tentu tak boleh hanya menjadi monopoli BCCF, juga
harus juga dimiliki oleh para pemangku kepentingan yang lain, diantaranya
Pemerintah kota, pelaku usaha, dan tentu saja masyarakat. Nah, pertanyaannya
adalah bagaimana mewujudkan asa menjadikan Bandung sebagai ibukota kreatif?
Darimana upaya ini harus dimulai? Pembuatan regulasi yang mendukung dan
mempermudah terciptanya iklim dan kondisi kreatif bisa menjadi langkah awal. Upaya
ini kemudian harus diikuti oleh penyediaan berbagai saran dan infrastruktur
pendukung yang memungkinkin aktifitas dan kegiatan kreatif tumbuh subur.
Langkah ketiga adalah dengan mengedukasi warga, agar senantiasa memiliki
kerangka berfikir kreatif dalam setiap aktifitas keseharian. Kreatifitas harus
dipahami sebagai sebuah communal behaviour serta tidak berumah di awan, yang
hanya bisa dijalankan dan dipraktekan oleh para pegiat kreatif. Dengan cara ini
Kreatifitas diharapkan menjadi kebiasan dalam praktek dan aktifitas masyarakat.
Agar
kegiatan dan aktifitas kreatif berdampak pada aktifitas ekonomi, perlu juga
dipikirkan kehadiran dan akses pasar, sehingga produk-produk kreatif memiliki
nilai ekonomi yang sebanding dengan upaya penciptaannya. Dalam hal ini, promosi
dan pemasaran memegang peranan penting. Selama ini, para pegiat kreatif berjibaku
dan berinovasi secara mandiri dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk
mereka. Tak hanya memikirkan inovasi produk, para pegiat kretaif juga dituntut
kreatif dalam memasarkannya. Tak hanya di pasar lokal juga di mancanegara.
Bahkan tanpa dukungan pemerintah pun, beberapa karya dan inovasi kreatif para pelaku
industri kreatif sudah mampu menembuh pasar global.
Jadi,
tunggu apa lagi. Ayo kita wujudkan Bandung sebagai Ibu kota kreatif tak hanya
untuk Indonesia, juga di kawasan Asia.
Itulah segmen yang dikupas dalam BCCF Magz (majalah
yang diterbitkan oleh BCCF) edisi Agustus 2012 dalam tajuk Bandung Ibukota
Kreativitas! Geliat aktivitas kreatif warga Bandung seolah tak pernah berhenti
dan kehabisan ide. Apalagi setelah ditetapkan sebagai pilot proyek Kota Kreatif
di Asia Timur tahun 2008, proses kreatif warga Bandung semakin bergairah dan menyebar
di seluruh penjuru. Jika di awal pertumbuhannya, pusat jeans Bandung ada di
sekitar Jl. Tamim, kini telah menyebar ke Cihampelas, Cigolewah dan sebagainya.
Begitu juga di sub sektor industri musik, lahir grup-grup baru dari berbagai
aliran. Seolah-olah, kota ini harus mengungguli Jakarta dan Surabaya. Berbagai
pagelaran musik berskala nasional maupun internasional di gelar di kota kembang
ini. Tidak mengherankan jika Bandung menyebut dirinya sebagai Ibukota
Kreativitas!.
Rasa hormat dan penghargaan tinggi memang layak
diterima oleh BCCF sebagai media komunikasi dan tempat berkumpulnya berbagai
komunitas kreatif kota Bandung dan sekitarnya. Semua sub sektor industri
kreatif yang diidentifikasi Kementrian
Perdagangan (14) plus kuliner merapat dan menjadi bagian aktif forum ini. BCCF berperan sangat besar dalam menjembatani
kepentingan semua komunitas kreatif di Bandung dengan berbagai pemangku
kepentingan (stakeholders). Karena
didalamnya ada komunitas perguruan tinggi yang dimotori oleh ITB terutama FSRD
(Fakultas Seni Rupa dan Desain) serta Sekolah Bisnis ITB. Komunitas jalanan dan
death metal yang biasanya tertutup, ternyata masuk di dalamnya.
BCCF bukan sekadar wadah komunitas kreatif yang
berbadan hukum. Tapi banyak kajian ilmiah yang berkait dengan pengembangan
sub-sub sektor ekonomi kreatif difasilitasi dan jadi keputusan politik dalam
membuka dan menata ruang-ruang publik seperti taman kota, halte bus dan
lain-lain. Sehingga fanatisme warga Bandung
kepada forum ini dinyatakan dalam beragam bentuk. Dari perkumpulan
penggemar sepeda, lahir bisnis baru penyewaan sepeda di waktu-waktu tertentu.
Belum yang terbilang prestisius semacam HelarFest yang telah berlangsung sejak
2008. Perkumpulan
Komunitas Kreatif Kota Bandung yang lebih dikenal dengan Bandung Creative
City Forum (“BCCF”) adalah organisasi lintas komunitas kreatif yang
dideklarasikan dan didirikan oleh Perseorangan, Wirausaha Kreatif, Lembaga
Nirlaba dan Komunitas di Kota Bandung pada tanggal 21 Desember 2008. BCCF
sendiri pada awalnya adalah sebuah forum komunikasi informal untuk koordinasi
dan komunikasi diantara komunitas kreatif di Bandung dalam rangka untuk
menyelenggarakan kegiatan Helar Festival 2008 (“Helarfest 2008”)
Sebagai
organisasi resmi, BCCF mempunyai maksud dan tujuan pada saat didirikannya BCCF sebagaimana
tertuang di dalam Anggaran Dasar Pendirian BCCF, yaitu sebagai berikut:
1.
Menjadi wadah penguatan masyarakat madani (civil
society) yang mandiri (independent) dan tidak terafiliasi baik langsung
atau tidak langsung dengan Organisasi Masa atau Partai Politik manapun, baik
ditingkat lokal atau nasional.
2.
Menjadi forum komunikasi, koordinasi dan usaha
bagi perseorangan atau badan usaha atau komunitas kreatif di Bandung.
3.
Menjadi forum bersama untuk memberikan daya
tawar lebih besar dalam penguatan ekonomi bagi para anggota, pelaku
ekonomi/industri kreatif dan kota Bandung sekitarnya.
4.
Menambah daya dorong pengembangan dan
pemberdayaan potensi kreatif warga Bandung dan sekitarnya.
5.
Memperkenalkan Bandung sebagai Kota Kreatif
terdepan, baik di tingkat nasional, regional dan internasional.
6.
Menjalin kerjasama baik ditingkat Nasional atau
Internasional untuk kepentingan pengembangan dan pembangunan ekonomi/industri
kreatif di Bandung.
7.
Mengembangkan kreatifitas sebagai upaya untuk
pemberdayaan ekonomi dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat sipil,
kelestarian ekosistem dan penghargaan terhadap keaneka-ragaman budaya.
Sebagai
organisasi lintas komunitas kreatif, BCCF ini didirikan oleh sebagian besar
adalah orang-orang atau komunitas kreatif yang ada di kota Bandung atau yang
bidang pekerjaan atau aktifitasnya bersinggungan sangat erat dengan dunia
kreatifitas dan inovasi. Para pendiri
dan anggota BCCF di awal pembentukan: BDA+Design, Urbane, Adiwilaga & Co,
Pixel People Project, LABO the Mori, Mahanagari, Sembilan Matahari,
Death
Rock Star, Tegep Boots, Invictus, Common Room Foundation, Bandung Arsitektur
Family (BAF), Bikers Brotherhood, KICK, Komunitas Sunda Underground, Bandung
Death Metal Sindikat, Solidaritas Independen Bandung, Ujung Berung Rebel,
Jendela Ide, Republic Entertainment, Saung Angklung Udjo, Pusat Studi Urban
Desain (PSUD), SAPPK ITB, Seni Rupa ITB, PSDP ITB, Eco- Ethno, Galeri Seni
Bandung, Open Labs dan sebagainya.
Pasca
Helarfest 2009, muncul beberapa nama baru
seperti Komunitas Air Fotografi, Komunitas Origami Indonesia, Komunitas
GANFFEST, INDDES ITB, Angklung Web Institute (AWI), Komunitas Picu Pacu,
Komunitas Mahasiswa Seni Rupa ITB, Bandung Flower Day, Bandung Affairs dan
sebagainya.
Rabu, 03 April 2013
ANTARA JOGJA, SOLO DAN BANDUNG
Rabu, April 03, 2013
Aneka Kerajinan, Aset, brand image, Budaya, Fesyen, Industri/ Ekonomi Kreatif, Obesesi, OVOP, Pariwisata, Wacana
No comments
Proses Kreatif di Pusat-pusat Kreatifitas - Bagian I
Hampir setiap kali membahas ekonomi kreatif, dua kota
utama : Jogja dan Bandung muncul sebagai bagiannya. Jogja dengan segala
sebutan : kota pelajar, wisata, kuliner (gudeg dan beragam jajanan khas),
budaya dan entah berapa lagi lainnya boleh disebut sebagai barometer dunia
kreatif di tanah air. Masih ingat kaos oblong “DAGADU” ? Kaos yang identik dengan kaum muda berlogo mata sesuai
namanya. Dagadu adalah bahasa plesetan dari kata matamu. Bagi masyarakat Jawa,
kata itu berkesan kasar atau tidak berbudaya. Di situlah letak ketajaman daya
kreasi pencipta merk ( A Noor Arief) yang telah dibajak berkali-kali, sampai
sekarang masih eksis berkreasi di sub sektor busana (fesyen/ fashion).
Selain memproduksi kaos, Dagadu juga memfasilitasi
beragam kegiatan kreatif di antaranya Lomba pembuatan video kreatif tentang
Jogja (Jocvec), membuat situs internet: http://blog.dagadu.co.id/ yang isinya khas dan semua dikasih nama dengan imbuhan MATA. Misalnya kolom yang bertajuk MATALALU yang berisi informasi masalalunya Dagadu untuk pemula maupun garda depan yang
punya tugas di bidang layanan konsumen (lakon). Tanpa bermaksud
melebih-lebihkan Dagadu (yang memang punya banyak kelebihan) atau Jogja (karena
bagian dari alumni di kota itu), saya menyoroti dagadu karena kejelian
mereka melihat banyak persoalan rumit dalam kacamata cerdas (smart) dan tetap
tersenyum
(smile). Dua hal yang membedakan “gali” Jogja dengan lainnya. Dagadu
adalah bahasa “gali” dan oleh mas Noor Arief sang pemilik merek dagang DAGADU
digali maknanya sampai benar-benar njogjani
alias pokoknya Jogja banget. Kesan sangar sang gali diubah total
dengan “senyum” yang representatif keramahan masyarakat Jogja.
Dalam hal penerapan Ekonomi Kreatif, Kota Jogja memakai logo di atas yang sudah cukup dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Jargon yang diusung adalah " NEVER ENDING ASIA". Kota ini memilih sub sektor kerajinan, fesyen, piranti keras dan lunak komputer sebagai andalan untuk menggerakkan ekonomi kreatifnya. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa Yogyakarta adalah kota seni dan budaya. Beragam peninggalan sejarah karya seni adiluhung seperti keraton dan tari langen bedaya-nya; pandangan spiritual tentang jalur imajinatif Merapi, Keraton dan Laut Selatan; munculnya nama kampung kerajinan seperti Batikan, Gamelan, Gemblakan, Kotagede dan lain-lain serta aneka kerajinan yang sudah memasyarakat seperti batik, olah kulit, ukir dan sebagainya.
Dari alasan di atas kemudian disusun 13 langkah untuk merealisasikannya:
- Mendorong lahirnta YOGYAtic sebagai komunitas produsen kerajinan sekaligus perintis pola pembinaan OVOP sehingga mendapat penghargaan Hiramatsu Award.
- Memfasilitasi sekretariat Yogya-IT
- Dalam RPJMD, salah satu programnya adalah pengembangan industri kreatif
- Kebijakan menuju Yogya Cyber Provinc
- Penyelenggaraan lomba desain produk kerjasama pusat dan daerah
- Mendorong kegiatan promosi penerbitan dan percetakan dalam bentuk bursa buku
- Memberikan apresiasi kepada kreator
- Melakukan sosialisasi kebijakan pengembangan industri kreatif
- Menyelenggarakan promosi produk industri kreatif di tingkat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan kegiatan tahunan Festival Kesenian Yogyakarta (FKY)
- Penyelenggaraan kegiatan tahunan Yogya Fashion Week
- Menyelenggarakan Cat Fish Day untuk meningkatkan konsumsi ikan nasional
- Menyelenggarakan pameran kuliner menu tradisional melalui dinas pariwisata
Mengurai kreatifitas anak-anak muda Jogja sepertinya tak akan ada habisnya. Setiap sudut kota punya sisi menarik untuk digali sisi kreatifnya. Pasar kerajinan di sepanjang Jl. Malioboro seolah bersambung dengan pasar jajanan di Jl. Mataram sampai Pasar Pathuk yang menyajikan bakpia hangat yang baru keluar dari oven para pembuatnya. Di sekitar pasar tradisional yang berada di tengah kota Jogja ini, kita bisa juga menikmati gudeg ala Yu Siyem yang telah dikenal sejak jaman perjuangan menegakkan kemerdekaan. Tidak heran jika Dagadu.co.id menyediakan laman khusus: kapan lagi ke Jogja untuk para alumni menapak-tilasi jejak Jogja dengan segala ragam kenangan yang melekat di hati.
Jika kaos Dagadu Jogja muncul di pertengahan 1990-an,
Bandung telah mendului sebagai pelopor pembuatan Indonesian Denim (jeans Bandung) dengan Jl. Tamim
sebagai icon utama. Beda dengan Jogja yang menggali habis budaya lokal,
Bandung cenderung memilih sebagai duplikator model jeans dari merek-merek
internasional yang sudah dikenal publik. Olah duplikasi ini berlangsung cukup
lama, sekitar dua dasawarsa sampai awal 2000-an ketika Jakarta mulai tertarik
bersaing dengan Bandung. Saat ketika produk konveksi dan garmen rumahan
mengalami booming. Setidaknya, kesan itu yang saya dapatkan di lapangan
sepanjang waktu mendampingi sentra konveksi Roworejo memasuki pusat-pusat
perdagangan barang konveksi dan garmen di Tanahabang dan Cipulir (Jakarta) atau
sekitar Jl. Embong Malang dan Jembatan Merah di Surabaya.
(bersambung: Solo dan Bandung)
Sabtu, 30 Maret 2013
OVOP & EKONOMI KREATIF
Sabtu, Maret 30, 2013
aktivitas, Aset, berpikir global, bertindak lokal, Budaya, Industri/ Ekonomi Kreatif, Inspiratif, kepedulian Pemerintah, keraifan budaya, Obesesi, OVOP, Wacana
No comments
Ada
dua gagasan dasar yang memiliki keserupaan dalam upaya mengembangkan potensi
ekonomi masyarakat yakni OVOP dan Ekonomi Kreatif. Beberapa tulisan sebelumnya
telah dibahas tentang OVOP. Kini giliran untuk mengupas faktor yang
mempengaruhi pilihan kebijakan pembangunan kewilayahan yaitu ekonomi kreatif
(Creative Economy) atau sering disebut juga dengan istilah Creative Industry).
Kedua istilah creative economy atau
industry saya anggap sama maknanya.
Definisi
ekonomi kreatif menurut Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekref) yaitu industri yang
berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk
menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan
pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Berdasar batasan ini
jelas sekali orientasi ekonomi kreatif adalah individual, SDM kreatif. Mungkin
ada pertanyaan, siapakah SDM kreatif itu ? Jawaban singkat : siapapun bisa dan
mungkin melakukan aktivitas ekonomi kreatif baik karena punya latar pendidikan
maupun berbakat kreatif.
Pertanyaan
berikutnya, apakah orang yang punya latar pendidikan dan bakat kreatif mampu
menyelenggarakan ekonomi kreatif? Jawaban singkat : tidak semua atau tidak
selalu. Mengapa? Banyak orang kreatif, mampu menghadirkan karya-karya kreatif
yang bernilai ekonomi tapi enggan atau tidak mampu menangkap peluang ekonomi
yang ada dalam karya-karyanya. Berkait dengan peluang, kita akan melihat di
sisi sebaliknya : tantangan dan/atau hambatan.
Dalam
buku Pengembangan Ekonomi Kreatif 2025 yang dipublikasikan (dapat diunduh gratis) oleh Kementrian
Pariwisata dan Ekonomi disebutkan bahwa di Amerika Serikat, Richard Florida
menggolongkan SDM kreatif sebagai strata (sosial-pen) baru yang disebut creative
class. Di era ekonomi baru ketika kreatifitas telah menjadi industri,
pekerja kreatif bukan hanya dari sektor seni. Di dalamnya ada juga ilmu pengetahuan (sains), teknologi, manajemen
dan lain-lain. Ada pendidik, peneliti,
insinyur, desainer, artis, musisi dam penghibur (entertainer). Mereka adalah orang-orang yang menghadirkan
ide-ide baru, teknologi baru, konten baru serta orang-orang yang mengandalkan
daya pikir dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah.
Berkembangnya
kegiatan berbasis kreativitas di Amerika Serikat, Inggris dan beberapa negara Asia
berupa kegiatan sub kontrak (outsourcing) yang kian menunjukkan
kematangannya membuat India dikenal sebagai negeri penghasil film (Bollywood)
dan piranti lunak. Sementara itu Korea Selatan dan China dikenal sebagai
produsen otomotif, barang-barang elektronik dan industri konten sejajar dengan
Jepang yang telah mendului. Singkat cerita kita akan menuju satu pertanyaan:
bagaimana dengan Indonesia ? Belum berkembang maksimal karena terkendala
beberapa hal utama:
- Banyak SDM kreatif di bidang artistik yang belum memahami secara menyeluruh “isi” kreativitas di era industri kreatif. Sehingga masyarakat awam menilai dunia artistis adalah ekslusif dan tidak merakyat ( masalah orientasi dan apresiasi – pen).
- SDM kreatif di luar bidang artistik (sains dan teknologi) terlalu mikroskopik dalam melihat keprofesionalannya sehingga cenderung berpola pikir mekanistik dan kurang inovatif ( masalah orientasi dan apresiasi – pen).
- SDM kreatif sering kekurangan sarana untuk melakukan eksperimen dan berekspresi sehingga hasil karyanya sering kurang kreatif dan inovatif (masalah apresiasi-pen).
Konsep
OVOP dan Ekonomi Kreatif menempatkan pembangunan SDM sebagai faktor penting. Sasaran
yang dituju pada konsep OVOP adalah produk lokal yang berorientasi global
dengan pendekatan komunal. Sementara itu, dalam ekonomi kreatif pendekatan yang
digunakan adalah individual. OVOP mengedepankan nilai tambah atas produk
(beberapa produk) yang sudah ada, ekonomi kreatif mengharuskan pembaruan atas
produk dan/atau jasa yang telah ada atau menghadirkan produk dan jasa yang
benar-benar baru dalam suatu proses inovatif. Perbedaan keduanya bisa
dijembatani dengan kebijakan politik pemerintah yang kondusif. Tumpang tindih
dan “perebutan wewenang” menangani kedua potensi kreatif masyarakat justru akan
mematikan jalan menuju Indonesia sejahtera, adil dan makmur (mungkin masih
bersambung).
Jumat, 29 Maret 2013
OVOP Indonesia ?
Jumat, Maret 29, 2013
aktivitas, brand, Budaya, Indonesia, Industri/ Ekonomi Kreatif, kepedulian Pemerintah, Lokal, Made in, masyarakat, OVOP, Wacana
No comments
Mampukah
koperasi menjadi fasilitator pengembangan OVOP di Indonesia? Bisa ya atau tidak.
Jawaban pasti akan banyak bergantung pada masing-masing koperasi yang ditunjuk
oleh Kementrian KUKM dalam menerjemahkan OVOP sehingga aplikasinya tepat
sasaran.
OVOP
di Indonesia
Sejauh
ini, Indonesia belum memiliki konsep dasar OVOP seperti OTOP di Thailand. Berikut adalah tentang OTOP.
Tujuan
OTOP di Thailand:
- Untuk membangun sebuah sistem database yang komprehensif, yang mengakomodasi informasi bagi setiap Tambon di Thailand
- Untuk mempromosikan produk lokal dari setiap Tambon, dan untuk memfasilitasi prosedur jual belinya.
- Untuk membawa teknologi internet ke desa-desa dan ini adalah titik awal dari Proyek Internet Tambon
- Untuk mendorong dan mempromosikan pariwisata di Thailand ke tingkat Tambon. Sehingga pendapatan akan dibagikan lebih besar kepada masyarakat pedesaan.
- Untuk membantu masyarakat pedesaan bertukar informasi, ide, dan meningkatkan komunikasi di berbagai Tambon.
Konsep
OVOP sangat fleksibel dan integratif. Artinya, setiap daerah atau wilayah dapat
menetapkan batasan dan tujuannya. Jika sasaran yang ingin dituju adalah skala
nasional, pendekatan yang digunakan biasanya top-down terutama berkait
dengan penyediaan anggaran. Kelemahan pendekatan ini, semangat kreatif yang
menjadi acuan pokok konsep dasar OVOP bisa tereliminasi oleh proses birokrasi
yang sangat panjang dan acapkali terjadi salah persepsi ketika harus diaplikasikan
kepada kelompok sasaran. Dalam istilah komunikasi, pendekatan top-bottom sering
menimbulkan denging (noise). Apalagi jika pejabat yang berkompeten
menangani di daerah tidak senada dan seirama karena “beda selera” atau
orientasi politik dengan yang di pusat. Lebih kacau lagi jika denging itu
ditambah bisikan yang bernada provokatif.
Sementara
itu, untuk mengaplikasikan konsep OVOP dengan pendekatan bottom up, kendala utama:
kelangkaan inisiatif karena beragam sebab. Yang paling klasik tentu soal
ketersediaan anggaran. Ibarat berdagang, harus ada modal finansial dulu sebelum
melangkah. Inisiatif akan muncul, mengikuti aliran dananya. Dengan kata lain,
jangan berharap ada inisiatif jika anggaran tidak tersedia. Kondisi seperti
inilah yang sering dijumpai ketika ada usulan dari ”bawah”. Belum lagi masalah tumpang tindih kebijakan antara satu dan
lain dinas atau kementrian.
Mengacu
pada gagasan dasar OVOP, produk yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki
kedekatan erat dengan budaya lokal dan bernilai tambah tinggi. Kerajinan adalah representatif untuk hal ini. Setidaknya
ada 2 atau dinas yang mungkin “merasa memiliki” yaitu dinas perindustrian/perdagangan,
dinas koperasi dan UKM serta dinas Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif. Bagi
daerah tertentu, mungkin ada penggabungan SKPD (satuan kerja pemerintah daerah)
yang terkait dengan aktivitas produktif dan kreatif masyarakat seperti Kabupaten
Kutai Kertanegara yang menggabungkannya jadi Disperindagkop (Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM). Semakin banyak dinas atau SKPD
yang merasa berkepentingan dengan dengan pengembangan kegiatan OVOP sebenarnya
semakin baik agar ada upaya maksimal untuk mewujudkannya.
Tetapi,
dalam realita sering berbeda. Setiap SKPD punya kepentingan dan biasanya tidak
mau digabungkan. Eksklusifitas kepentingan inilah jadi satu masalah serius bagi
pengembangan aplikasi OVOP di banyak daerah, termasuk Kabupaten Kebumen. Karena
itu, pada acara Temu Solusi OVOP Jawa Tengah 22 Februari 2013 lalu, Deputi
Bidang Pengkajian Sumber Daya Manusia Kementrian Koperasi dan UKM tidak
menyebut kerajinan anyaman pandan Kebumen sebagai bagian yang telah
diprogramkan pada 2013. Selain carica di Wonosobo dan bordir di Kudus, gula
kelapa di Cilacap, batik Solo, kain sarung goyor di Pemalang dan Klaten, tenun troso
Jepara dan kerajinan ikan pari di Boyolali.
Inilah
yang menjadi satu pertanyaan besar saya dan teman-teman di lapangan, mengapa
ketika dalam peringatan Hari Koperasi 2012 di Kabupaten Kebumen, pemecahan
rekor Muri atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen dibebankan kepada para
perajin anyaman pandan ? Selanjutnya, mengapa aktivitas itu dipindahkan
lokasinya dari area publik (alun-alun Kebumen) ke area pribadi (pabrik Dubexcraft) ?
Pertanyaan paling krusial, mengapa untuk acara seakbar itu para perajin
tidak diapresiasi secara layak ? Apakah hal ini yang jadi penyebab
utama tidak masuknya kerajinan anyaman pandan Kabupaten Kebumen yang telah
membawa Tasikmalaya, Jogja dan Bali menjadi pemasok utama ekspor kerajinan
anyaman pandan ke dalam program OVOP??
Bagaimana
mungkin mengaplikasikan satu program pembangunan yang diadopsi dari negara lain
tanpa pemahaman memadai tentang faktor kultural
masyarakatnya? Jepang diakui sebagai negara maju yang masih kuat menjaga
tradisi dan budaya masyarakatnya. Sebagai
negara yang pernah dijajah Jepang,
sedikit banyak, masyarakat Indonesia memahami kondisi itu sebagai nilai tambah
kemajuan Jepang dibandingkan dengan Eropa maupun Amerika Serikat. Disiplin dan
kerja keras adalah tradisi masyarakat Jepang yang tidak mudah diaplikasikan di
Indonesia. Apalagi di masa sekarang, kebanyakan dari pemimpin formal di semua
lini, tidak menjadikan kedua tradisi itu sebagai pemacu semangat yang menumbuh-kembangkan
tantangan-tantangan kreatif sebagai realisasi prinsip dasar OVOP di bidang
pengembangan sumber daya manusia.
Praktik
yang lazim terjadi justru sebaliknya. Orang-orang yang memelihara prinsip
kemandirian (sama dengan menjaga kemerdekaan) justru tidak disukai oleh para
pengambil keputusan politik (baca sebagai pejabat publik) karena akan mengganggu kepentingan pribadi
atau kelompoknya. Kekusutan ini diperparah dengan pola rekrutmen pejabat publik
yang sarat praktik KKN dan semakin telanjang. Dan lebih kusut lagi karena
semakin jarang ditemui pejabat publik mau bekerja sama dengan orang-orang yang menjaga independensi dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal.
OVOP
adalah program idealistik dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Potensi kreatif masyarakat berbasis kultural dan bernilai tambah tinggi. Penghormatan
atas hal itu adalah pengembangan aktivitas produktif tanpa merusak tradisi yang
dijunjung tinggi oleh masyarakat lokal. Modernisasi dimungkinkan pada sisi
rancang bangun produk (product design) dengan pendekatan
teknologi informasi. Sebelum hal ini diterapkan, masyarakat lokal harus
dikondisikan dengan nilai-nilai budaya yang terdapat pada teknologi itu.
Sehingga tidak menimbulkan cultural shock yang kemudian akan mematikan potensi
budaya lokal secara sistematik.
Kemudahan
mengakses informasi internet dari telepon selular yang telah menjangkau ke
desa-desa di satu sisi menumbuhkan harapan baru bagi pengembangan potensi lokal.
Di sisi lain, hal itu justru akan menjadi bencana kebudayaan ketika pengguna
tidak memahami nilai-nilai kultural yang ada di dalamnya. Sangat mungkin
terjadi perubahan pola pikir yang semula produktif menjadi konsumtif. Dalam
koteks OVOP, potensi lokal yang seharusnya menjadi titik pijak dan pacu
pengembangan aspek ekonomi dapat berbalik arah menjadi faktor perusak utama
potensi itu. Di sinilah sisi menarik dari konsep aplikasi OVOP di berbagai negara.
Kita (Indonesia) bisa mewujudkan gagasan brilian Mr. Morihiko Hiramatsu dengan sikap hati-hati, tapi tanpa curiga.
Jika Thailand mampu dengan OTOP, suatu saat mungkin kita akan meluncurkan ODOB
(One District One Brand) atau justru sebaliknya, benar-benar jadi bodo
? (bersambung)
Kamis, 14 Maret 2013
Pasar Senggol 2010: Sederhana Tapi Manis
Kamis, Maret 14, 2013
Aset, Budaya, Cerita, Industri/ Ekonomi Kreatif, Kebumen, Kegiatan, Kreatif, Lokal
1 comment
Panggung utama
Pasar Senggol :Sekaten ala Kebumen yang Tengah Bersolek
Belajar dari pengalaman dan kegagalan di
masa lampau adalah salah satu ciri manusia berfikiran maju. Pada pelaksanaan
kegiatan yang sama di tahun 2010 ini, salah satu tokoh masyarakat di sekitar
tempat berlangsungnya acara tahunan PASAR SENGGOL, Yahya Mustofa, mengungkapkan
banyak hal tentang pengalaman menyelenggarakan acara ritual budaya masyarakat
di sekitar Pasar Selang Kebumen. Mengikuti anjuran Bupati saat itu, H.M.
Nashirudin Al Mansyur yang menginginkan penyelenggaraannya mirip atau sama
dengan Sekaten Jogja ternyata berbuah kekecewaan yang berlarut. Semula ia
kurang bergairah saat disinggung kemungkinan pelaksanaannya di tahun 2010.
Selain faktor
keuangan yang mengalami difisit cukup besar, sampai saat ini Panitia
Penyelenggara yang terdiri dari tokoh masyarakat dan perangkat desa di Selang,
Adikarso dan sekitarnya belum mampu menuntaskan laporan kegiatan itu. Kendala
lain adalah kegagalan menghadirkan band metal asal Bandung "Power Slave"
kepada para penggemar musik rock Kebumen setelah dilarang tampil oleh aparat
kepolisian justru di saat akhir waktu. Pelarangan di sela check sound punggawa
band yang senafas dengan grup band kondang asal Inggris, LED ZEPPELIN. Artinya,
ada " keanehan "
di balik pelarangan yang berdalih keamanan. Singkat kata, misi mengangkat
peristiwa budaya masyarakat lokal ini "gagal".
Karena itu,
setelah kami berdiskusi luas dan menemukan satu titik temu pemikiran bahwa jika
peristiwa budaya itu harus dilakukan dengan cara dan suasana yang berbeda.
Perbedaan skala prioritas dan yang menggembirakan adalah keterlibatan komunitas
pelaku seni budaya lokal yang aktif berproses dan memiliki komitmen kuat untuk
mengembangkan Pasar Senggol sebagai bagian dari upaya pengembangan potensi
ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen. Khususnya dalam hal seni pertunjukan,
periklanan, kerajinan, pasar seni dan barang antik serta layanan komputer dan
piranti lunak dalam sebuah "kawasan industri kreatif" bernama PASAR
SENGGOL 2010. Yang Muda Ceria,
Yang Tua Bahagia. Bukan
sekadar all about Kebumen.
Tapi Kebumen Ngethek alias It's Truly Kebumen ... yakin
gologokin.
Obrolan tengah malam jelang pelaksanaan
Tradisi masyarakat Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dalam
memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW cukup beragam. Di tlatah (wilayah kuasa
kerajaan) Mataram masyarakat mengenal Grebek Maulid yang disebut Sekaten. Jika
perayaan di Ngayogyakarta Hadiningrat (Jogja) diawali dengan kirab pusaka
keraton dan berakhir dengan keluarnya gunungan kembar simbol kemakmuran. Hal
serupa terjadi juga di Solo. Bedanya, simbolisasi di Keraton Surakarta
adalah tradisi "angon kebo bule" Kyai dan Nyai Slamet. Meski kurang
faham dengan makna dibalik nama pasangan kerbau itu dan peristiwa yang
mengiringi, nampaknya keselamatan dan kemakmuran jua yang menjadi tujuan utama
tradisi tersebut.
Peristiwa sama di Desa Selang dan sekitarnya disebut Pasar
Senggol. Sejak berpuluh tahun yang lalu, masyarakat di sekitar pasar
tradisional desa Selang semisal Adikarso, Kalirejo, Panjer, Kebumen dan
sebagainya menjadikan acara itu sebagai peristiwa budaya lokal dalam rangkaian
kegiatan memperingati hari besar keagamaan Islam. Dalam peristiwa itu, muncul
nama tokoh utama : Kramaleksana.
Dari penuturan Yahya Mustofa, sosok Kramaleksana adalah “pahlawan” yang membuka
lahan bagi sejumlah masyarakat di wilayah itu. Dia adalah prajurit Mataram yang
ditugaskan bersama sejumlah pasukan lain untuk memperluas wilayah kekuasaan. Di
sisi inilah beragam cerita heroik dan mistis muncul sebagai bagian tradisi
masyarakat tersebut. Karena itu, model perayaannya sangat mirip dengan gaya
Jogja ketimbang Solo.
Layaknya sebuah pasar malam, ada berbagai kegiatan yang
melingkupinya. Sebagai ajang bisnis para pedagang kaki lima, bakul jajanan,
pedagang mainan anak dan sebagainya. Yang tidak pernah ketinggalan adalah
sebagai ajang mencari jodoh, arena perebutan kekuasaan preman lokal dengan segala
nuansanya dan beragam pernak-pernik kehidupan malam. Karena itu, dimensi religi
yang seharusnya lebih menonjol dibanding tradisi yang belum dikaji dalam
penelitian ilmiah acapkali terabaikan.
Yang menarik dari penyelenggaraan tahun ini adalah adanya
sentuhan manajemen hiburan. Sebagai tokoh sentral, Yahya Mustofa yang tahun
kemarin mendapat Upakarti Bidang Kepoloporan Pemuda, pemilik Dubex Handicraft
dan sejumlah unit usaha lain serta Ketua Umum Hipando (Himpunan Perajin Anyaman
Indonesia) mengundang orang yang bertugas khusus menangani manajemen hiburan
tersebut. Tema pokok yang ditawarkan sebagaimana dituturkan Fauzan adalah “All about Kebumen”.
Bila diterjemahkan bebas mungkin jadi “ pokoknya asal
Kebumen”. Tema itulah yang menarik perhatian kami, Komunitas Ego. Ada
kegairahan tersendiri di saat kami tengah mengangkat produk budaya lokal yang
kian terpinggirkan seperti Kethoprak Pesisiran dan Rodat, Jamjaneng dsb. Sekaligus
memberi pencerahan kepada orang-orang di dinas kebudayaan setempat yang
mendefinisikan kesenian atau budaya lokal identik
dengan irama yang rancak dan dalam suguhan jingkrak-jingkrak.
Lebih bergairah lagi ketika kami mendengar langsung dari
Yahya Mustofa, bahwa panggung utama akan dilengkapi fasilitas multi media.
Pucuk dicinta, ulam tiba. Angan kami mengembara ke desa Brecong Buluspesantren.
Di sana ada tokoh seni kethoprak pesisiran, Bambang Kethoprak.
Bergegas kami kunjungi beliau dan menawarkan kerja sama. Kolaborasi antara seni
drama tradisional dan teater modern dengan kesepakatan bahwa soal teknis pentas
akan dibicarakan khusus dengan ahlinya, Putut AS dan kawan-kawan Komunitas Ego yang
selama ini berproses di Jogja dengan nama Sanggar Ilir atau Wayang Mika L mas
Kaji Habeb.
Bambang Kethoprak
Entah sebab
apa, kami mendapat informasi dari Seksi Hiburan, Gobeth Arief Budiman bahwa
Polres Kebumen hanya memberi ijin 2 hari dari 6 hari yang dijadwalkan.
Mendengar kabar itu, kami terkulai lemas. Setelah menunda sehari, akhirnya kami
memberi tahu mas Bambang bahwa pentas kolaboratif di Pasar Senggol 2010 urung
dilaksanakan karena alokasi waktunya sangat pendek. Hanya 30 menit. Panggung
utama yang semula didesain knock down karena berada di persimpangan
jalan Kutoarjo dan Cendrawasih harus dipindahkan ke lokasi aman di tanah kosong
di belakang deretan tenda pedagang. Lengkap sudah kecewa kami kepada Panitia,
khususnya Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berkesan “ hanya mau mengunduh
tanpa kesediaan mengunggah” atas
potensi kreatifitas warga masyarakatnya. Apalagi ditambah penuturan Yahnya
Mustofa, bahwa ketika mengajukan ijin kegiatan itu di Pemkab, timnya di – ping
pong.
Meski pada
akhirnya waktu penyelenggaraan yang dijadwalkan selama 6 hari menjadi nyata,
tapi dengan persiapan yang hanya lima hari membuat gairah kami tak mudah
dipulihkan. Dan karena undangan ditujukan kepada Panitia Gelar Panggung Teater
(GPT) 2010, kami harus menindak-lanjuti undangan Panitia Pasar Senggol itu
kepada seluruh pengisi acara yang ada di Kabupaten Kebumen. Dari tujuh komunitas teater
pengisi acara GPT 2010, hanya dua yang siap pentas yakni Teater Gerak dari
STAINU dan Teater Putra Bangsa (Tetrasa) STIE Putra Bangsa Kebumen. Sebagai
wujud tanggung jawab dan kepedulian, Komunitas Ego mendampingi proses latihan
dan pentas Tetrasa di hari ke 2 penyelenggaraan Semarak Pasar Senggol 2010.
Lega di balik kecewa mendalam. Sambil berjalan pulang kami meneriakkan “selesai sudah masa
janji, selesai sudah tugas menanti “
seperti prajurit pulang dari medan laga. Sekedar melepas penat dari rasa yang
kian menggumpal dari waktu ke waktu.
Sanggar Ilir - Imakta membuka kebuntuan berteater dengan
GPT 2009 dan 2010