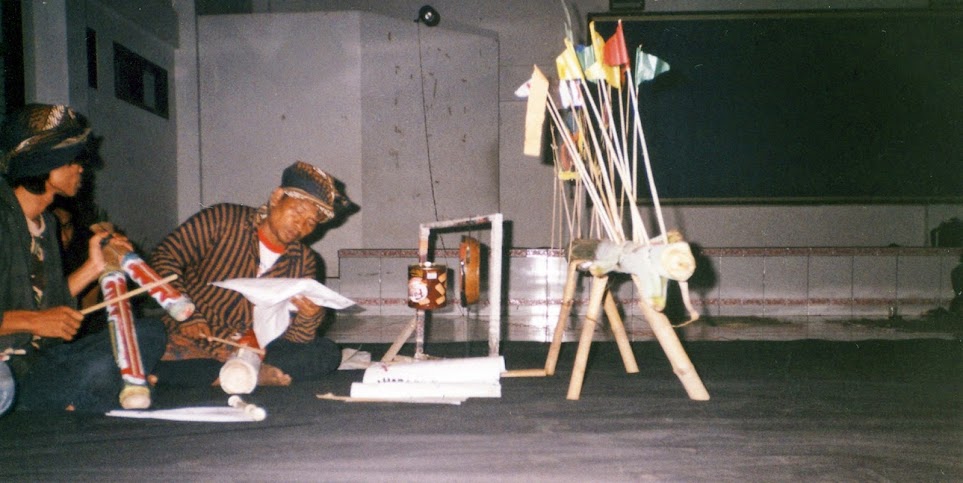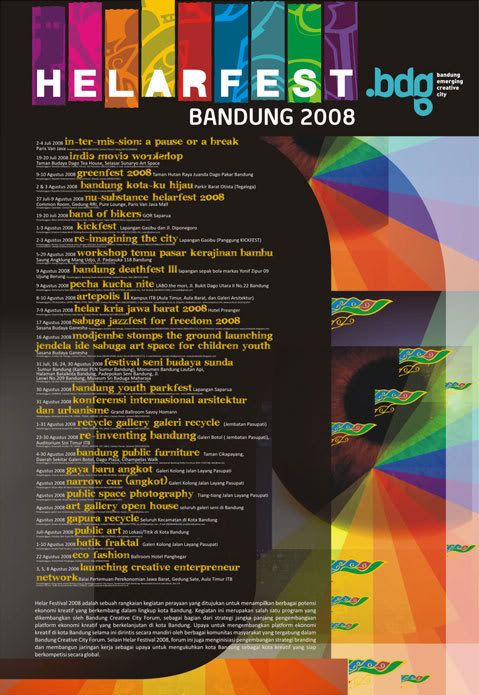Bandung kota kreatif bukan hanya slogan dan baru
dirintis. Sejak dulu, Kota Kembang yang sering disebut juga sebagai Paris van
Java telah menunjukkan beragam aktivitas kreatif warganya. Di era 1980-an, jauh
waktu sebelum ekonomi/ idustri kreatif digagas, Bandung sudah punya Depot
Kreasi Seni Bandung (DKSB) dengan alm. Harry Rusli sebagai motornya dari
rumahnya di Jl. Supratman sebagai markas besar. Dari grup musik eksperimental ini muncul satu single
hit berjudul Nyamuk Malaria. Sementara itu, di ujung jalan itu ada beragam
jenis kuliner khas yang menjadikan daerah Supratman Ujung sebagai pusat jajanan
khas Bandung. Musik, seni pertunjukan dan kuliner adalah pilar ekonomi kreatif
yang tengah menjadi trend baru ekonomi di banyak Negara.
Bandung Ibukota Kreativitas?
Reputasi Bandung
sebagai destinasi wisata, lokasi perguruan tinggi terkemuka, pusat mode dan
busana, serta kota yang melahirkan beragam band/kelompok musik progresif, telah
berdampak pada tumbuhnya industri kreatif yang didukung oleh ketersediaan
beragam sumber daya. Bandung jadi Ibukota Kreatif?
APA sih yang kurang
dari Kota Bandung sebagai kota kreatif? Rasanya semua persyaratan untuk menjadi
kota kreatif sudah dimilki Bandung. Sebut saja, hampir seluruh profesi kreatif
bisa ditemukan di Bandung, sejak profesi yang high profil seperti arsitektur,
clothing dan distro, pembuat program komputer, animator, hingga pemBuat film dan
musik. Belum lagi iklim yang mendukung, dengan banyaknya pagelaran dan hajatan
kreatif yang digelar dan sepanjang tahun. Untuk yang terakhir ini, para pegiat
kreatif Bandung sudah dua kali menggelar hajatan Helarfest, tahun 2008 dan
2009. Tahun 2010, ada Semarak.bdg yang digelar di sekitar kawasan Braga. Belum
lagi gelaran seperti Bandung World Jazz Festival, dan Pasar Seni ITB.
Situs
Departemen Perdagangan menginformasikan industri kreatif menyumbang rata-rata
6,3% terhadap produk domestik bruto Indonesia selama periode 2002-2006. Suatu
jumlah yang tidak main-main karena pada 2010, target kontribusi meningkat
menjadi 7,9%. Setelah kekayaan sumber daya alam tidak lagi dapat menjadi
penopang perekonomian nasional, ditambah sulitnya produk sektor usaha berbasis
sumber daya alam lainnya bersaing dengan negara lain karena kalah kompetitif, maka
masa depan Indonesia mungkin hanya bisa diselamatkan melalui ekonomi kreatif
yang berbasis kekuatan ‘human capital’ yang kreatif dan inovatif.

Lantas,
dari angka kontribusi 7,9 % ini, seberapa besar yang disumbang Bandung? Meski
tidak tersedia data yang cukup memadai, namun diyakini Bandung berkontribusi
dominan. Terlebih, karena para pegiat di Bandung juga sudah memiliki kesadaran
untuk beserikat dan berorganisasi dalam payung Bandung Creative City Forum atau
BCCF.
Bandung
Creative City Forum (BCCF) yang berdiri sejak tahun 2008, beranggotakan para
pegiat kreatif dari beragam latar belakang profesi antara lain arsitek,
desainer, pekerja seni, pekerja musik, akademisi, praktisi & pekerja TI,
pelaku usaha pariwisata, dan jurnalis. Seluruh
kegiatan BCCF bersifat nirlaba dan diperuntukan sepenuhnya untuk pengembangan
kota Bandung dalam bidang dan karya kreatif. BBCF juga merupakan mitra
strategis Pemerintah Kota Bandung dalam membawa Bandung sebagai kota kreatif
dengan kompetensi internasional di benua Asia.
Tujuan
untuk menjadikan Bandung sebagai ibukota kreatini bukan hal yang mustahil untuk
diwujudkan. Semangat ini, tentu tak boleh hanya menjadi monopoli BCCF, juga
harus juga dimiliki oleh para pemangku kepentingan yang lain, diantaranya
Pemerintah kota, pelaku usaha, dan tentu saja masyarakat. Nah, pertanyaannya
adalah bagaimana mewujudkan asa menjadikan Bandung sebagai ibukota kreatif?
Darimana upaya ini harus dimulai? Pembuatan regulasi yang mendukung dan
mempermudah terciptanya iklim dan kondisi kreatif bisa menjadi langkah awal. Upaya
ini kemudian harus diikuti oleh penyediaan berbagai saran dan infrastruktur
pendukung yang memungkinkin aktifitas dan kegiatan kreatif tumbuh subur.
Langkah ketiga adalah dengan mengedukasi warga, agar senantiasa memiliki
kerangka berfikir kreatif dalam setiap aktifitas keseharian. Kreatifitas harus
dipahami sebagai sebuah communal behaviour serta tidak berumah di awan, yang
hanya bisa dijalankan dan dipraktekan oleh para pegiat kreatif. Dengan cara ini
Kreatifitas diharapkan menjadi kebiasan dalam praktek dan aktifitas masyarakat.
Agar
kegiatan dan aktifitas kreatif berdampak pada aktifitas ekonomi, perlu juga
dipikirkan kehadiran dan akses pasar, sehingga produk-produk kreatif memiliki
nilai ekonomi yang sebanding dengan upaya penciptaannya. Dalam hal ini, promosi
dan pemasaran memegang peranan penting. Selama ini, para pegiat kreatif berjibaku
dan berinovasi secara mandiri dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk
mereka. Tak hanya memikirkan inovasi produk, para pegiat kretaif juga dituntut
kreatif dalam memasarkannya. Tak hanya di pasar lokal juga di mancanegara.
Bahkan tanpa dukungan pemerintah pun, beberapa karya dan inovasi kreatif para pelaku
industri kreatif sudah mampu menembuh pasar global.
Jadi,
tunggu apa lagi. Ayo kita wujudkan Bandung sebagai Ibu kota kreatif tak hanya
untuk Indonesia, juga di kawasan Asia.
Itulah segmen yang dikupas dalam BCCF Magz (majalah
yang diterbitkan oleh BCCF) edisi Agustus 2012 dalam tajuk Bandung Ibukota
Kreativitas! Geliat aktivitas kreatif warga Bandung seolah tak pernah berhenti
dan kehabisan ide. Apalagi setelah ditetapkan sebagai pilot proyek Kota Kreatif
di Asia Timur tahun 2008, proses kreatif warga Bandung semakin bergairah dan menyebar
di seluruh penjuru. Jika di awal pertumbuhannya, pusat jeans Bandung ada di
sekitar Jl. Tamim, kini telah menyebar ke Cihampelas, Cigolewah dan sebagainya.
Begitu juga di sub sektor industri musik, lahir grup-grup baru dari berbagai
aliran. Seolah-olah, kota ini harus mengungguli Jakarta dan Surabaya. Berbagai
pagelaran musik berskala nasional maupun internasional di gelar di kota kembang
ini. Tidak mengherankan jika Bandung menyebut dirinya sebagai Ibukota
Kreativitas!.
Rasa hormat dan penghargaan tinggi memang layak
diterima oleh BCCF sebagai media komunikasi dan tempat berkumpulnya berbagai
komunitas kreatif kota Bandung dan sekitarnya. Semua sub sektor industri
kreatif yang diidentifikasi Kementrian
Perdagangan (14) plus kuliner merapat dan menjadi bagian aktif forum ini. BCCF berperan sangat besar dalam menjembatani
kepentingan semua komunitas kreatif di Bandung dengan berbagai pemangku
kepentingan (stakeholders). Karena
didalamnya ada komunitas perguruan tinggi yang dimotori oleh ITB terutama FSRD
(Fakultas Seni Rupa dan Desain) serta Sekolah Bisnis ITB. Komunitas jalanan dan
death metal yang biasanya tertutup, ternyata masuk di dalamnya.
BCCF bukan sekadar wadah komunitas kreatif yang
berbadan hukum. Tapi banyak kajian ilmiah yang berkait dengan pengembangan
sub-sub sektor ekonomi kreatif difasilitasi dan jadi keputusan politik dalam
membuka dan menata ruang-ruang publik seperti taman kota, halte bus dan
lain-lain. Sehingga fanatisme warga Bandung
kepada forum ini dinyatakan dalam beragam bentuk. Dari perkumpulan
penggemar sepeda, lahir bisnis baru penyewaan sepeda di waktu-waktu tertentu.
Belum yang terbilang prestisius semacam HelarFest yang telah berlangsung sejak
2008. Perkumpulan
Komunitas Kreatif Kota Bandung yang lebih dikenal dengan Bandung Creative
City Forum (“BCCF”) adalah organisasi lintas komunitas kreatif yang
dideklarasikan dan didirikan oleh Perseorangan, Wirausaha Kreatif, Lembaga
Nirlaba dan Komunitas di Kota Bandung pada tanggal 21 Desember 2008. BCCF
sendiri pada awalnya adalah sebuah forum komunikasi informal untuk koordinasi
dan komunikasi diantara komunitas kreatif di Bandung dalam rangka untuk
menyelenggarakan kegiatan Helar Festival 2008 (“Helarfest 2008”)
Sebagai
organisasi resmi, BCCF mempunyai maksud dan tujuan pada saat didirikannya BCCF sebagaimana
tertuang di dalam Anggaran Dasar Pendirian BCCF, yaitu sebagai berikut:
1.
Menjadi wadah penguatan masyarakat madani (civil
society) yang mandiri (independent) dan tidak terafiliasi baik langsung
atau tidak langsung dengan Organisasi Masa atau Partai Politik manapun, baik
ditingkat lokal atau nasional.
2.
Menjadi forum komunikasi, koordinasi dan usaha
bagi perseorangan atau badan usaha atau komunitas kreatif di Bandung.
3.
Menjadi forum bersama untuk memberikan daya
tawar lebih besar dalam penguatan ekonomi bagi para anggota, pelaku
ekonomi/industri kreatif dan kota Bandung sekitarnya.
4.
Menambah daya dorong pengembangan dan
pemberdayaan potensi kreatif warga Bandung dan sekitarnya.
5.
Memperkenalkan Bandung sebagai Kota Kreatif
terdepan, baik di tingkat nasional, regional dan internasional.
6.
Menjalin kerjasama baik ditingkat Nasional atau
Internasional untuk kepentingan pengembangan dan pembangunan ekonomi/industri
kreatif di Bandung.
7.
Mengembangkan kreatifitas sebagai upaya untuk
pemberdayaan ekonomi dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat sipil,
kelestarian ekosistem dan penghargaan terhadap keaneka-ragaman budaya.
Sebagai
organisasi lintas komunitas kreatif, BCCF ini didirikan oleh sebagian besar
adalah orang-orang atau komunitas kreatif yang ada di kota Bandung atau yang
bidang pekerjaan atau aktifitasnya bersinggungan sangat erat dengan dunia
kreatifitas dan inovasi. Para pendiri
dan anggota BCCF di awal pembentukan: BDA+Design, Urbane, Adiwilaga & Co,
Pixel People Project, LABO the Mori, Mahanagari, Sembilan Matahari,
Death
Rock Star, Tegep Boots, Invictus, Common Room Foundation, Bandung Arsitektur
Family (BAF), Bikers Brotherhood, KICK, Komunitas Sunda Underground, Bandung
Death Metal Sindikat, Solidaritas Independen Bandung, Ujung Berung Rebel,
Jendela Ide, Republic Entertainment, Saung Angklung Udjo, Pusat Studi Urban
Desain (PSUD), SAPPK ITB, Seni Rupa ITB, PSDP ITB, Eco- Ethno, Galeri Seni
Bandung, Open Labs dan sebagainya.
Pasca
Helarfest 2009, muncul beberapa nama baru
seperti Komunitas Air Fotografi, Komunitas Origami Indonesia, Komunitas
GANFFEST, INDDES ITB, Angklung Web Institute (AWI), Komunitas Picu Pacu,
Komunitas Mahasiswa Seni Rupa ITB, Bandung Flower Day, Bandung Affairs dan
sebagainya.